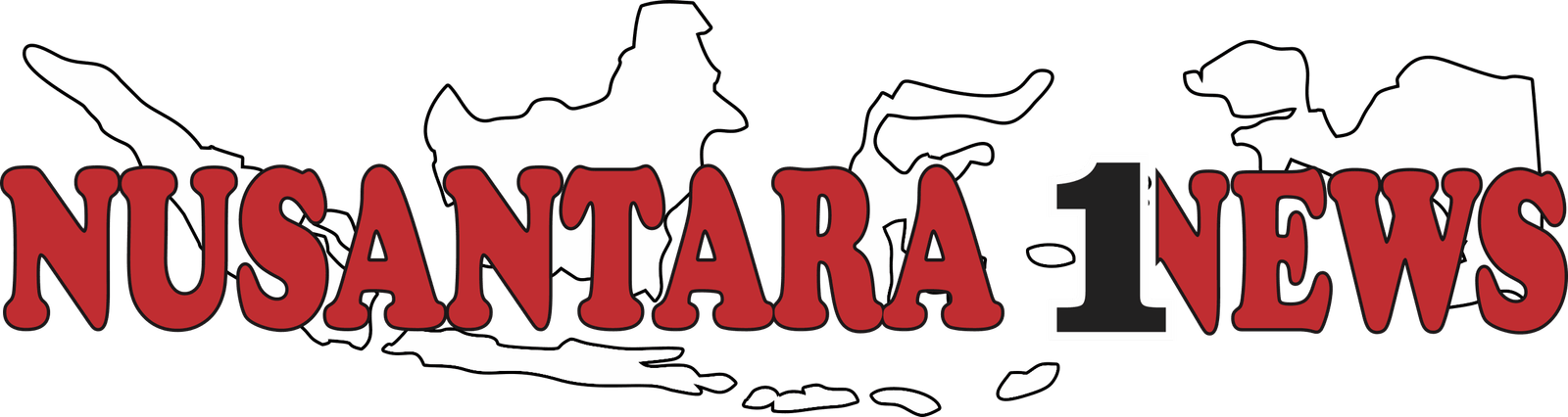Nusantara1News – Mongabay Krisis Pengelolaan Gambut, Ancaman Ekologi dan Dampaknya di Riau.
Pemandangan di tepian kanal selebar enam meter di Kayong Utara, Kalimantan Barat, mencerminkan kondisi ekosistem gambut yang semakin kritis. Pohon-pohon kering bercampur akar yang berserakan bertumpuk dengan gambut yang tercabik, sementara air kanal berwarna cokelat pekat bergetar akibat deru alat berat yang bekerja di kawasan konsesi perkebunan kayu. Situasi ini menggambarkan betapa rentannya lahan gambut, salah satu ekosistem lahan basah di Indonesia.
Baca Juga : TNI AU Persiapkan SDM dan Drone Baru untuk Amankan Natuna Utara
Di Riau, kondisi gambut juga semakin memprihatinkan. Dari total 4,9 juta hektar kawasan hidrologis gambut, lebih dari setengah tutupan hutan telah lenyap dalam kurun waktu 1990-2020. Awalnya seluas 3,5 juta hektar, kini hanya tersisa 1 juta hektar akibat konversi untuk perkebunan, pertambangan, pertanian, dan pemukiman.
Tingkat kerusakan semakin mengkhawatirkan, di mana hanya 24.000 hektar atau 0,49% dari total kawasan yang masih dalam kondisi baik. Sebagian besar, sekitar 4,1 juta hektar, mengalami kerusakan ringan. Kerusakan ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan air, menjadikan gambut lebih rentan terhadap kebakaran. Data dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menunjukkan bahwa antara 2015 hingga 2020, lebih dari 284.000 hektar kawasan hidrologis gambut di Riau terbakar.
Menurut Okto Yugo Setiyo, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), ancaman terhadap gambut akan terus meningkat dengan rencana pembukaan 20 juta hektar hutan, yang sebagian besar berada di wilayah gambut. Laporan akhir tahun 2024 dari Jikalahari menyoroti bahwa korporasi menjadi aktor utama dalam perusakan gambut, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan lahan atas nama kelompok masyarakat.
Dalam setahun terakhir, Jikalahari masih menemukan praktik penebangan hutan alam, kebakaran lahan, serta konflik antara perusahaan dan masyarakat di sekitar kawasan gambut. Deforestasi juga terjadi di konsesi hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan sawit, dengan 50% kawasan mengalami degradasi.
Kerusakan gambut juga berdampak pada peningkatan frekuensi banjir di Riau. Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah yang kerap dilanda banjir dalam dua tahun terakhir, terutama di jalur lintas timur yang menghubungkan Riau dan Jambi. Deforestasi yang tinggi berkontribusi terhadap meluasnya dampak banjir, sebagaimana diungkapkan oleh Okto. Analisis Jikalahari menemukan bahwa dalam enam tahun terakhir, telah terjadi 261 kejadian banjir di 592 lokasi di seluruh Riau, seiring dengan hilangnya 2,5 juta hektar tutupan hutan alam antara 2000 hingga 2023.
Selain memperparah banjir, pembukaan hutan gambut juga memicu konflik antara manusia dan satwa liar. Sejak 2018, setidaknya 13 orang meninggal akibat serangan harimau Sumatera, dengan 11 kasus terjadi di dalam konsesi hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Mayoritas insiden ini terjadi di kawasan gambut Kerumutan, salah satu hutan rawa gambut terluas di Riau.
Eksploitasi lahan basah di pulau-pulau kecil juga memunculkan ancaman baru, di mana pembukaan hutan rawa gambut dan pembuatan kanal mempercepat intrusi air laut. Hal ini berdampak pada perekonomian masyarakat yang bergantung pada ekosistem gambut serta mempercepat laju abrasi daratan di pulau-pulau tersebut.
Sigit Sutikno, Ketua Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau, menyoroti dampak masifnya pembangunan kanal di lahan gambut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017, panjang total drainase buatan di Riau mencapai 7.576,18 kilometer, dengan 1.248,31 kilometer di antaranya melintasi kawasan hidrologis gambut.
“Pembuatan kanal di gambut mempercepat degradasi. Penurunan permukaan tanah (subsiden) menjadi indikator utama kerusakan. Banjir di Pelalawan, misalnya, terlihat dari air berwarna cokelat pekat menandakan bahwa gambut tak lagi mampu menyimpan air. Situasi ini akan terus terjadi setiap tahun,” ungkapnya.
Pemulihan Gambut Lamban, Sementara Kerusakan Kian Meluas
Kerusakan ekosistem gambut terus bertambah parah, sementara upaya pemulihannya berjalan lambat. Menurut Sigit Sutikno, keberhasilan restorasi gambut sulit diukur karena berbagai kendala di lapangan.
“Pemulihan gambut masih jauh dari harapan,” ujarnya.
Sigit menyoroti bahwa upaya rehabilitasi lahan basah terlalu bergantung pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Namun, lembaga ini hanya beroperasi di tingkat pusat tanpa kehadiran di tingkat provinsi maupun kabupaten, sehingga kewalahan menangani kerusakan gambut yang luas.
Di daerah, program pemulihan gambut yang dilakukan BRGM hanya melalui skema tugas perbantuan, seperti melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Akibatnya, pelaksanaannya belum masif dan kurang terstruktur.
Di Riau, pemerintah daerah telah membentuk Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah (TRGMD). Namun, menurut Sigit, tim ini belum mampu memberikan dampak signifikan dalam mempercepat pemulihan gambut.
Salah satu penyebabnya adalah komposisi tim yang hanya terdiri dari birokrat dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tanpa melibatkan banyak pihak. Bahkan, TRGMD dinilai minim aksi nyata di lapangan.
Sigit mengusulkan agar BRGM dijadikan lembaga permanen dan TRGMD diubah menjadi OPD khusus, serupa dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Jika seperti itu, kinerjanya bisa lebih terstruktur dan pemulihan gambut bisa berjalan lebih cepat,” katanya.
Sementara itu, Okto Yugo Setiyo dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menilai bahwa peran BRGM semakin melemah sejak mendapat tambahan tugas untuk memulihkan mangrove. Fokus utama mereka terhadap restorasi gambut, khususnya di dalam konsesi perusahaan kehutanan, mulai terabaikan.
Menurutnya, tanggung jawab pemulihan gambut seharusnya tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk merestorasi lahan gambut yang telah terbakar di dalam konsesi mereka. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, yang kemudian direvisi dengan PP 57 Tahun 2016.
Namun, temuan Jikalahari bersama koalisi dari delapan provinsi menunjukkan bahwa restorasi gambut yang dilakukan oleh perusahaan masih lebih mengutamakan kepentingan industri. Misalnya, pembangunan sekat kanal yang tidak memenuhi standar, sehingga air hanya bertahan saat musim kemarau dan mengalir keluar saat musim hujan.
Dampak dari sistem ini dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang sebagian besar bergantung pada lahan gambut di luar konsesi perusahaan. “Perusahaan sepenuhnya mengendalikan tata air di dalam kanal mereka,” kata Okto.
Temuan lain menunjukkan bahwa alih-alih memulihkan lahan gambut yang telah terbakar, banyak perusahaan justru kembali menanaminya dengan komoditas seperti akasia, eukaliptus, dan sawit. Laporan mengenai praktik ini telah dirilis sejak 2019 oleh koalisi dari enam provinsi, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Kembali ke Regulasi: Penguatan Perlindungan Gambut
Okto Yugo Setiyo menegaskan bahwa upaya perlindungan gambut harus kembali berpegang pada regulasi yang ada, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Salah satu ketentuannya adalah alokasi minimal 30% dari total Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) sebagai area dengan fungsi lindung, terutama di bagian puncak dan sekitarnya.
Aturan ini mengikat pemerintah daerah yang memiliki kawasan gambut, mewajibkan mereka untuk mengadopsinya ke dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).
Di Riau, RPPEG telah tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 803 Tahun 2022. Dokumen ini mencakup pemetaan luas serta kondisi gambut, strategi pemulihan, rencana aksi, serta panduan pelaksanaan, termasuk pembagian tugas antar perangkat daerah.
Selain melalui RPPEG, perlindungan gambut juga seharusnya diperkuat dalam Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, hingga kini, Pemerintah Riau belum melakukan revisi RTRW setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi terhadap beberapa pasal bermasalah dalam aturan tersebut.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah luas kawasan lindung gambut yang hanya ditetapkan 25.000 hektar—jauh di bawah ketentuan 30% dari total 4,9 juta hektar gambut di Riau.
Pada 2019, Jikalahari bersama koalisi mengajukan gugatan terhadap ketentuan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018. Dua bulan setelahnya, MA mengabulkan permohonan tersebut.
Kini, revisi Perda RTRW 2018-2038 telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan menunggu pembahasan di DPRD. “Kita akan terus mengawal proses ini,” tegas Okto.
Bukan untuk Pengembangan Food Estate di Lahan Gambut
Pantau Gambut melakukan studi pemantauan pada 30 titik lokasi yang digunakan untuk pengembangan pangan skala besar (food estate) di Kalimantan selama periode 2020-2023, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini, yang menggunakan lahan bekas proyek pengembangan lahan gambut (PLG) seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah (Kalteng), menunjukkan hasil yang mengecewakan. Hampir seluruh lahan gambut terbuka ternyata tidak cocok untuk budidaya padi.
Lola Abas, Koordinator Pantau Gambut, menjelaskan bahwa dari tiga blok eks-PLG di Kalteng yang mencakup 243.216 hektar, hanya 1% yang cocok untuk pertanian, sementara sisanya menunjukkan kesesuaian sedang hingga rendah. Banyak lahan yang sudah dibuka akhirnya dibiarkan terbengkalai atau diubah menjadi perkebunan sawit milik perusahaan swasta.
Menurut Lola, pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian seharusnya hanya dilakukan pada lahan gambut dangkal (kurang dari satu meter) yang telah dibudidayakan sebelumnya, dengan pendekatan yang sangat hati-hati, menggunakan teknologi pengelolaan air yang tepat dan menyesuaikan dengan karakteristik gambut dan jenis tanaman yang akan ditanam.
Lola juga mengusulkan agar pemerintah lebih mengutamakan pendekatan swasembada pangan berbasis lokal, yang sesuai dengan kondisi lahan gambut, dan lebih melibatkan masyarakat daripada korporasi dalam pengelolaan lahan gambut.
Sementara itu, Azwar Maas, Peneliti Gambut Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, mengingatkan bahwa tidak boleh ada kegiatan yang merusak kawasan gambut yang masih utuh, terutama yang memiliki kubah. Kubah gambut ini sangat penting untuk kesehatan tanah dan sebagai sumber air selama musim kemarau.
Baca Juga : Gotong royong TNI bersama warga perbatasan RI-Malaysia
Azwar menambahkan, lahan gambut di Merauke, Papua, yang digunakan untuk food estate adalah bekas rawa lama yang telah terangkat, yang ditandai dengan banyaknya karat besi di permukaannya. Karakteristik ini mirip dengan gambut di Lampung, namun gambut di Lampung telah dimanfaatkan lebih dari 100 tahun, sementara Merauke baru saja dibuka.
Azwar mengimbau agar pemerintah melibatkan perguruan tinggi dalam proyek food estate skala besar dan melakukan riset yang mendalam. Proses ini harus melibatkan pengetahuan tentang tanah, bukan hanya urusan engineering atau sipil. Jika lahan gambut sudah terbuka, restorasi ke kondisi semula hampir mustahil. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Prabowo, perlu menata ulang peraturan terkait pelestarian dan pemanfaatan gambut.