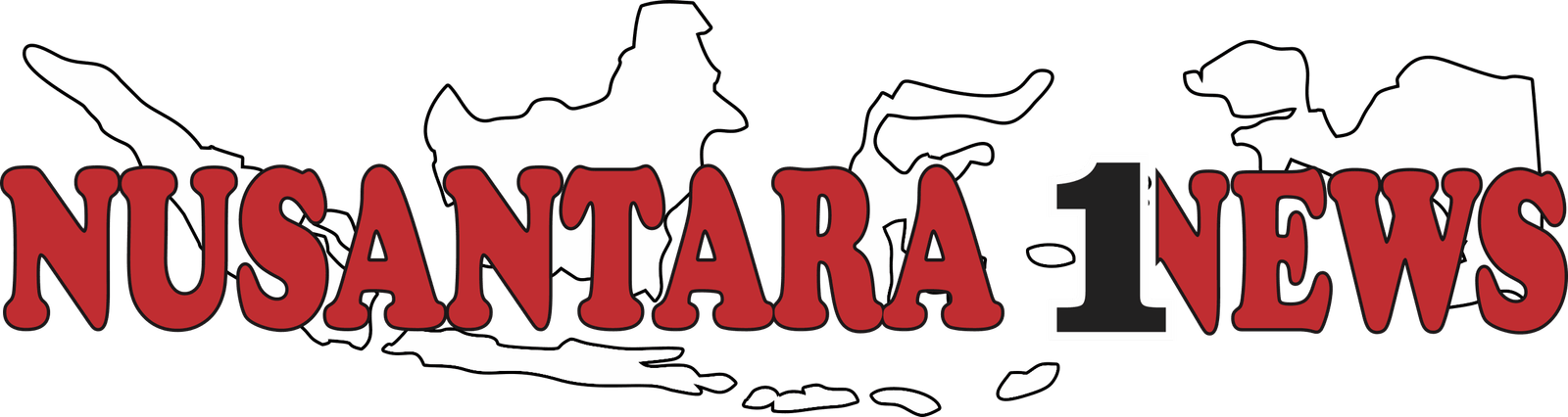Nusantara1News – Wacana pembukaan 20 juta hektar hutan guna memenuhi kebutuhan pangan dan energi menuai kritik. Kebijakan ini dinilai berpotensi mengancam kemandirian pangan masyarakat adat serta meningkatkan risiko bencana ekologis. Sebagai alternatif, sejumlah pihak menyarankan pemerintah lebih fokus memperkuat peran petani dalam produksi pangan serta mengembangkan energi berbasis sumber daya terbarukan.
Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, menilai kebijakan ini bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam pengurangan emisi karbon dan pengelolaan hutan berkelanjutan.
Baca Juga : Langkah Konkret KLHK Atasi Udara Buruk: Tutup TPA Liar dan Modifikasi Cuaca
“Jika proyek ini berjalan atas nama pangan, energi, dan air, maka ini akan menjadi salah satu proyek legalisasi deforestasi terbesar sepanjang sejarah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah gagal dalam melindungi hutan karena terus memisahkan masyarakat dari lingkungan mereka. Hutan yang selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat adat justru mengalami privatisasi di bawah status kawasan hutan negara. Setelahnya, izin pengelolaan justru diberikan kepada korporasi untuk keperluan perkebunan, tambang, atau industri kayu.
Dampaknya, ketidakseimbangan ekosistem semakin parah, alih fungsi hutan terus terjadi, dan krisis iklim makin tak terhindarkan. Data Walhi menunjukkan bahwa sepanjang 2015–2022, bencana ekologis yang oleh BNPB dikategorikan sebagai bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 10.160 orang meninggal atau hilang.
“Sebanyak 43,3 juta jiwa mengalami luka, harus mengungsi, atau terdampak langsung akibat bencana sepanjang periode tersebut,” tambah Uli.
Kerugian ekonomi akibat bencana ini pun tidak kecil. Negara disebut menanggung beban hingga Rp101,2 triliun akibat dampak hidrometeorologi.
Ketika negara membahas pangan, energi, dan air dalam kerangka bisnis, keadilan bagi rakyat dan lingkungan semakin sulit terwujud. Dalam praktiknya, pendekatan ini justru mengesampingkan pangan lokal, hak masyarakat adat, dan kearifan budaya dalam menjaga kedaulatan pangan.
Menurut para pengkritik, model produksi pangan berbasis bisnis lebih banyak menguntungkan korporasi dibandingkan petani kecil. Bahkan, pemerintah kerap menggunakan aparat keamanan demi melancarkan proyek-proyek besar yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Dampaknya bukan sekadar deforestasi atau konflik agraria. Hilangnya biodiversitas hanyalah bagian dari masalah yang lebih besar bahkan nyawa masyarakat bisa melayang saat mereka berjuang mempertahankan tanah mereka. Negara menggunakan pendekatan keamanan agar proyek berjalan tanpa hambatan,” ujar seorang aktivis.
Martin Hadiwinata, Koordinator Nasional FIAN Indonesia, menilai pola pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan saat ini mirip dengan era Orde Baru. Kala itu, program revolusi hijau dipaksakan kepada masyarakat dengan pendekatan yang mengutamakan kepentingan korporasi.
“Dulu, petani dipaksa menggunakan benih tertentu, pupuk kimia, dan pestisida melalui tekanan aparatur negara. Memang sempat terjadi swasembada pangan, tapi hanya bertahan lima tahun. Setelah itu, ketergantungan pada beras semakin besar, dan swasembada pun runtuh,” jelasnya.
Dalam satu dekade terakhir (2013–2023), jumlah petani dengan lahan kurang dari setengah hektar atau petani gurem terus meningkat.
Menurut Martin, narasi swasembada pangan yang digaungkan pemerintah saat ini hanyalah ilusi.
Jika rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi direalisasikan, dampaknya akan sangat besar. Prosesnya tak sederhana dan bisa merombak total sistem pangan nasional. Sayangnya, pemerintah seakan mengabaikan peran strategis petani kecil yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan.
Minim Transparansi, Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan Sarat Masalah
Hingga kini, keterbukaan informasi terkait proyek pembukaan 20 juta hektar hutan masih sangat terbatas. Lokasi pasti hutan yang akan dibuka pun belum jelas. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 5 Desember 2014, hutan yang masuk dalam proyek ini terdiri dari 15,53 juta hektar yang belum berizin dan 5,07 juta hektar yang sudah memiliki izin.
Dari hutan yang telah berizin, sekitar 1,9 juta hektar merupakan bagian dari program perhutanan sosial. Sementara itu, hutan yang belum berizin terdiri dari 2,29 juta hektar hutan lindung dan 13,24 juta hektar hutan produksi.
Amalya Reza Oktaviani, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia, menduga bahwa pembukaan hutan ini akan difokuskan di Kalimantan dan Papua, mengingat kedua wilayah tersebut masih memiliki tutupan hutan yang cukup luas.
Yang mengejutkan, menurut Amel sapaan akrabnya adalah dimasukkannya hutan lindung dalam rencana proyek ini.
“Hutan lindung seharusnya tetap berfungsi sebagai kawasan perlindungan, bukan dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur,” tegasnya.
Dalam periode 2020–2024, Trend Asia mencatat adanya deforestasi legal dan terencana di kawasan hutan yang telah berizin, dengan luas mencapai 1,49 juta hektar di Kalimantan dan 408.000 hektar di Papua. Jika proyek ini terus berjalan, risiko bencana ekologis seperti banjir dan longsor akan semakin meningkat, terutama di Kalimantan yang sudah berkali-kali mengalami bencana akibat alih fungsi hutan.
Dari total lebih dari 120 juta hektar hutan di Indonesia, masih terdapat 36,6 juta hektar kawasan hutan yang belum memiliki penetapan tata batas yang jelas.
Amel menilai, rencana pembukaan 20 juta hektar hutan ini sangat bermasalah, terutama karena banyak kawasan hutan yang statusnya belum pasti.
“Seharusnya pemerintah memastikan kejelasan status kawasan hutan terlebih dahulu, bukan malah meluncurkan program cadangan pangan dan energi di tengah berbagai permasalahan yang belum terselesaikan,” pungkasnya.
Perkuat Petani dan Sumber Lokal, Tinggalkan Pendekatan Gagal
Martin menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam kebijakan pertanian dengan lebih berfokus pada manusia. Penggunaan bibit lokal serta sistem pertanian yang telah berkembang di masyarakat seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar mengejar proyek berskala besar. Menurutnya, pendekatan lama yang selama ini diterapkan terbukti tidak efektif dan harus ditinggalkan.
Pangan bukan hanya soal hasil produksi, tetapi juga mencerminkan budaya petani dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan aspek ini dalam menyusun kebijakan.
Martin juga menekankan pentingnya keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan terkait pertanian. Kebijakan semestinya dirancang bersama para petani, bukan dibuat sepihak oleh pemerintah dan hanya menguntungkan korporasi. Contohnya, program food estate yang banyak dikritik karena mengabaikan peran petani lokal.
Selain itu, pemerintah perlu memperluas perspektif dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketergantungan pada beras harus dikurangi dengan mengoptimalkan sumber pangan lokal yang beragam dan melimpah di Indonesia.
Menurut Martin, kebijakan pertanian harus lebih berpihak pada petani kecil. Ia menyoroti Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disahkan pada 2013, tetapi hingga kini belum benar-benar diterapkan.
“Undang-undang itu hanya ada di atas kertas, tapi tidak pernah dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penggunaan istilah dalam kebijakan pangan. Menurutnya, istilah “kedaulatan pangan” lebih tepat dibandingkan “swasembada pangan” karena lebih menekankan pemenuhan pangan dengan cara yang menghormati lingkungan serta berpihak kepada petani, nelayan, dan masyarakat adat.
Jika pemerintah tetap memilih membuka hutan untuk proyek pangan dan energi, risikonya sangat besar. Berdasarkan perhitungan Trend Asia, langkah ini bisa menyebabkan emisi karbon hingga 4,9 miliar ton dan deforestasi sebesar 38% dari total 20 juta hektar yang direncanakan. Angka ini diambil dari sejarah deforestasi akibat izin usaha pemanfaatan hutan tanaman hingga 2021.
Sebagai alternatif, Trend Asia mendukung dan mendorong inisiatif berbasis komunitas dalam memenuhi kebutuhan energi. Sejumlah daerah di Indonesia telah berhasil mengembangkan sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), yang lebih ramah lingkungan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.
Dukung Inisiatif Lokal, Bukan Proyek Energi yang Mengorbankan Masyarakat
Menurut Amel, pemerintah seharusnya mendorong inisiatif energi berbasis masyarakat daripada sekadar membangun pembangkit listrik sesuai kepentingannya sendiri.
Ia mencontohkan pengalaman di Mentawai, di mana masyarakat setempat awalnya telah mendapatkan pelatihan dan modul untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara mandiri. Setiap rumah memiliki modul sendiri, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Namun, setelah satu tahun, pemerintah justru memperkenalkan proyek pembangkit listrik biomassa dengan janji listrik menyala 24 jam.
Akibatnya, warga menjual modul PLTS mereka karena percaya akan beralih ke sumber energi baru. Sayangnya, pembangkit biomassa tersebut hanya bertahan enam bulan, dan masyarakat akhirnya kehilangan akses listrik sama sekali.
Bagi Amel, kebijakan top-down semacam ini justru membuat masyarakat semakin dirugikan. Sebelumnya mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan energi sendiri, tetapi intervensi pemerintah malah membuat mereka kehilangan kemandirian.
Di tingkat global, negara-negara seperti Inggris kini menghadapi kesulitan dalam memasok bahan baku untuk pembangkit bioenergi mereka. Sementara itu, Indonesia justru mengekspor bahan baku bioenergi ke Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Menurut Amel, Indonesia seharusnya belajar dari tantangan yang dihadapi negara lain sebelum terjebak dalam ketergantungan industri bioenergi skala besar.
Di dalam negeri, berbagai inisiatif lokal telah berhasil mengembangkan solusi energi mandiri. Contohnya, Masyarakat Adat Seberuang di Kampung Silit, Kalimantan Barat, yang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di dalam hutan adat mereka seluas 4.000 hektar. Tanpa dukungan dana dari pemerintah, mereka membangun sistem energi secara gotong royong dan mengelola kebutuhan pangan serta energi secara mandiri.
Baca Juga : Prabowo Beri Amnesti untuk Puluhan Ribu Narapidana
Namun, keberlanjutan inisiatif ini terancam ketika pemerintah mengeluarkan izin konsesi tambang emas di hulu hutan mereka. Masyarakat akhirnya harus berjuang melawan tambang tersebut demi melindungi hutan mereka. Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil mempertahankan wilayahnya dan mendapatkan pengakuan negara atas hutan adat tersebut.
Amel menegaskan bahwa Indonesia perlu berhenti mengandalkan transisi energi yang berbasis pada industri lahan skala besar.
“Semua bioenergi industri pasti bergantung pada lahan. Jika transisi energi masih berorientasi pada eksploitasi lahan, maka itu bukan solusi, melainkan masalah baru,” pungkasnya.