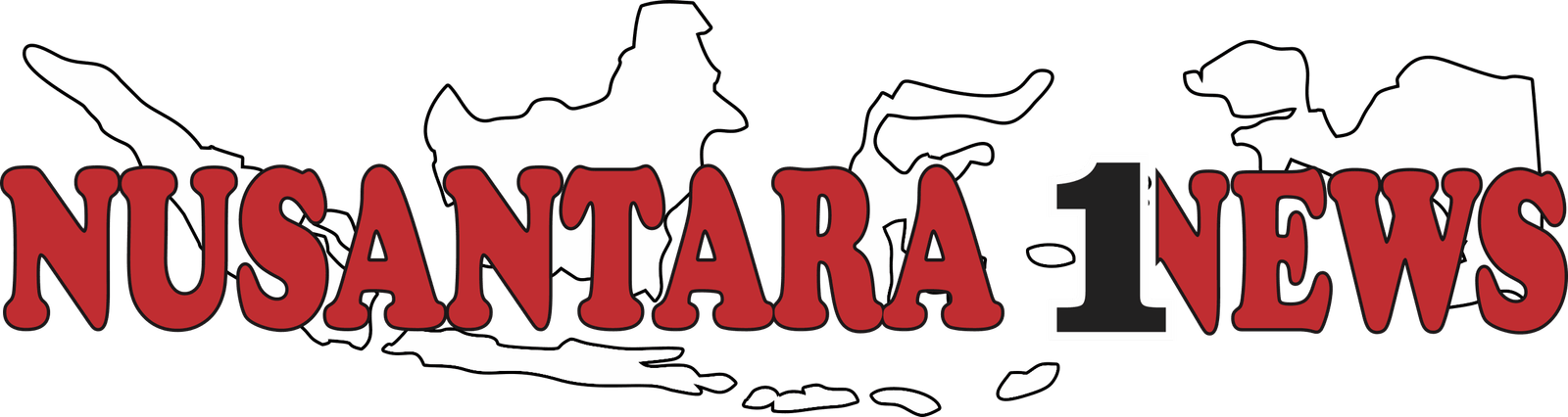Nusantara1News – Hutan mangrove memiliki peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, termasuk bagi pulau-pulau kecil di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Namun, keberadaannya kini semakin terancam akibat alih fungsi lahan untuk berbagai proyek berskala besar, termasuk yang berlabel ‘proyek strategis nasional’.
Di Pulau Tanjung Sauh, misalnya, kawasan mangrove yang dahulu menutupi wilayah pesisir kini tergerus akibat pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proyek ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial bagi masyarakat setempat. Hal serupa terjadi di Moro, Kabupaten Karimun, di mana warga dikejutkan oleh pemasangan pancang di area mangrove untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh perusahaan Singapura.
Baca Juga : Pemerintah Diingatkan untuk Bijak dalam Melakukan Efisiensi Anggaran
Menurut Hendrik Hermawan, Pendiri Akar Bhumi Indonesia (ABI), hampir seluruh wilayah Kepulauan Riau, terutama Batam, mengalami kerusakan mangrove akibat reklamasi, industrialisasi, serta ekspansi permukiman yang masif, termasuk pembangunan waduk.
Di pesisir Kampung Panau Nongsa, Kota Batam, ABI menemukan sekitar delapan hektar hutan mangrove telah hilang demi pembangunan pabrik baja. “Reklamasi di kawasan ini berlangsung besar-besaran. Hutan mangrove tertimbun, kondisi laut memburuk, dan para nelayan kehilangan mata pencaharian mereka,” ujarnya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, proses reklamasi yang dilakukan dinilai tidak mengikuti prosedur yang ketat, minim pengawasan, dan dilakukan tanpa perlindungan pantai yang memadai. Akibatnya, material reklamasi menyebabkan peningkatan kekeruhan air laut yang berpotensi merusak ekosistem perairan.
Sementara itu, Soni Herianto, Ketua ABI, menekankan bahwa dengan luas kurang dari 100.000 hektar, Batam tergolong pulau kecil yang rentan terhadap dampak lingkungan. Hilangnya hutan mangrove semakin meningkatkan risiko bencana, seperti abrasi pantai yang terjadi lebih cepat tanpa adanya perlindungan alami dari pohon mangrove.
Selain itu, nelayan setempat juga mengalami penurunan hasil tangkapan karena ikan kehilangan habitat pemijahan. “Ketika gugusan mangrove di pulau-pulau kecil menghilang, area tangkapan nelayan pun berkurang drastis,” jelasnya, Selasa (11/2/25).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberadaan mangrove bukan sekadar soal ekosistem, tetapi juga perlindungan bagi masa depan pulau itu sendiri. “Jika hutan mangrove hilang, maka keberlanjutan pulau-pulau kecil akan terancam.”
atam Kehilangan Sebagian Besar Hutan Mangrove, Hanya Tersisa 1.743 Hektar
Berdasarkan data dari BPDAS Sei Jang Duriangkang, Batam memiliki salah satu kawasan mangrove terluas kedua di Kepulauan Riau (Kepri), namun sayangnya, Batam juga tercatat sebagai daerah dengan laju kehilangan mangrove yang sangat cepat.
Secara keseluruhan, ekosistem mangrove di Kepri meliputi 67.417 hektar, dengan sebaran di beberapa daerah: Kota Tanjungpinang (1.448 hektar), Kota Batam (18.335 hektar), Bintan (8.553 hektar), Lingga (19.056 hektar), Karimun (14.059 hektar), Natuna (4.873 hektar), dan Kabupaten Anambas (1.093 hektar).
Pada awalnya, hutan mangrove di Batam mencakup sekitar 27% dari total luas Batam yang mencapai 41.500 hektar. Namun, kerusakan yang terus berlangsung menyebabkan luas hutan mangrove Batam menyusut drastis hingga hanya tersisa 4,2%, atau sekitar 1.743 hektar. Jika tren ini tidak segera dihentikan, BPDAS memperingatkan bahwa jumlahnya akan terus berkurang.
Menurut informasi dari Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BPDAL), lebih dari 800 hektar hutan mangrove hilang akibat berbagai aktivitas, termasuk sekitar 650 hektar di kawasan Tembesi yang telah beralih fungsi untuk proyek-proyek seperti pembangunan waduk.
Kerusakan mangrove tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga di Tanjungpinang. Dalam sepuluh tahun terakhir, sekitar 40% hutan mangrove di daerah ini hilang akibat pencemaran dan reklamasi. BPDAS mengungkapkan, kerusakan ini berpotensi mengancam mata pencaharian nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan seperti kepiting, ikan, dan udang.
Tahun lalu, Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Sumatera menetapkan PT TMS sebagai tersangka korporasi terkait perusakan mangrove di Tanjung Berakit Tiangwangkang, Kelurahan Tembesi, Batam. Luas area mangrove yang rusak mencapai 22 hektar. Direktur PT TMS, yang berinisial DS, dijadikan tersangka dengan barang bukti berupa 11 truk dan satu bulldozer.
DS diancam dengan Pasal 98 Ayat (1) jo. Pasal 116 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 119 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta UU 06/2023 tentang Perppu 2/2022 terkait Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
Peran Mangrove dalam Menjaga Ekosistem dan Meningkatkan Kesejahteraan Pesisir
Rahimah Zakia, Fasilitator Program Yayasan Ecology, menekankan bahwa mangrove memiliki fungsi yang sangat vital, terutama bagi pulau-pulau kecil. “Mangrove berperan penting sebagai pelindung pantai, mengurangi risiko banjir rob, dan ancaman lainnya,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Perempuan dan Mangrove: Membangun Kedaulatan Ekologi dan Ekonomi di Pulau Bintan, pada Selasa (11/2/25).
Selain itu, mangrove juga lebih efektif dalam menyerap karbon dibandingkan hutan daratan. Oleh karena itu, hilangnya kawasan mangrove dapat memicu peningkatan suhu global dan memperburuk ancaman abrasi pantai.
Yarsi Efendi, seorang Dosen Ekologi dan Pengetahuan Lingkungan FKIP Biologi Universitas Riau Kepulauan Batam, menyatakan bahwa kerusakan mangrove di pulau-pulau kecil Batam sudah menjadi masalah yang berlangsung lama. Sayangnya, ekosistem ini yang juga menjadi habitat penting bagi biota laut seperti kepiting dan udang, terus mengalami tekanan.
“Kerusakan mangrove berarti hilangnya zona penyangga yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem pesisir, pantai, dan daratan,” kata Yarsi dalam tulisan berjudul Mangrove Kian Tergerus Pembangunan.
Aktivis lingkungan Parid Ridwanuddin, yang juga menjabat di Bidang Politik Sumber Daya Alam LHKP PP Muhammadiyah, menekankan bahwa penyelamatan mangrove membutuhkan dukungan politik yang kuat. Salah satu langkah penting adalah mengevaluasi proyek-proyek yang berpotensi merusak mangrove, termasuk proyek-proyek strategis nasional (PSN).
Menurut Parid, secara hukum, hutan mangrove sudah dilindungi sebagai bagian dari kesatuan ekosistem yang harus dipertahankan. Misalnya, dalam Undang-Undang Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, ada larangan untuk mengalihfungsikan kawasan mangrove menjadi area industri, dengan ancaman hukuman penjara.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 73, UU ini menetapkan sanksi bagi mereka yang merusak mangrove, termasuk bagi pihak yang tidak melakukan mitigasi bencana. Pelaku perusakan mangrove dapat dijerat dengan hukuman di bawah regulasi tersebut,” jelasnya.
Parid menegaskan, mangrove harus dilindungi karena statusnya yang sangat penting sebagai bagian dari ekosistem esensial. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap semua pembangunan yang berpotensi merusak ekosistem tersebut.
Meskipun Indonesia memiliki regulasi yang kuat untuk melindungi mangrove, kenyataannya di lapangan hal ini sering kali tidak terlaksana dengan baik. “Seharusnya, setiap proyek, termasuk PSN, yang mengancam mangrove harus dievaluasi. Namun, masalah utama terletak pada political will dari pemerintah,” pungkasnya.
Walhi Kritik Tata Kelola Mangrove di Indonesia, Soroti Perbedaan Data dan Regulasi
Walhi mengkritik buruknya tata kelola mangrove di Indonesia, dengan menyoroti tiga masalah utama yang ditemukan dalam pengelolaannya. Berdasarkan situs resmi Walhi, masalah pertama adalah ketidakkonsistenan data mengenai mangrove.
Laporan Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan luas kawasan mangrove mencapai 2.320.609,89 hektar, namun hanya 30,32% yang berada dalam kondisi baik. Di sisi lain, Peta Mangrove Nasional (PMN) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2021 menyebutkan data yang berbeda, dengan luas mangrove lebih dari 3.364.080 hektar, dan 92,78% dalam kondisi sangat baik (lebat). Selain itu, PMN juga mencatatkan adanya potensi wilayah mangrove seluas 756.183 hektar.
Masalah kedua yang disoroti oleh Walhi berkaitan dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU 11/2020) yang direvisi pada 2023. Pasal 5 dalam UU ini mengatur tentang legalisasi panas bumi di wilayah perairan, yang menurut Walhi dapat membuka peluang bagi perusakan mangrove.
Baca Juga : Australia Larang Anak di Bawah 16 Tahun Gunakan Media Sosial
Ketiga, Walhi juga menyoroti Pasal 3-7 dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa zona inti dalam ekosistem mangrove dapat dialihkan untuk kepentingan proyek-proyek strategis nasional (PSN).
Dalam laporan yang berjudul Negara Melayani Siapa?, Walhi menggambarkan lemahnya perlindungan terhadap mangrove di Indonesia. Laporan tersebut mencatat bahwa hingga tahun 2040, area pesisir yang akan direklamasi mencapai 3.527.120,17 hektar, sementara hanya 52.455,91 hektar wilayah mangrove yang mendapat perlindungan. “Perbandingan ini sangat ironis jika dibandingkan dengan luas area proyek reklamasi,” ungkap Walhi dalam laporannya.