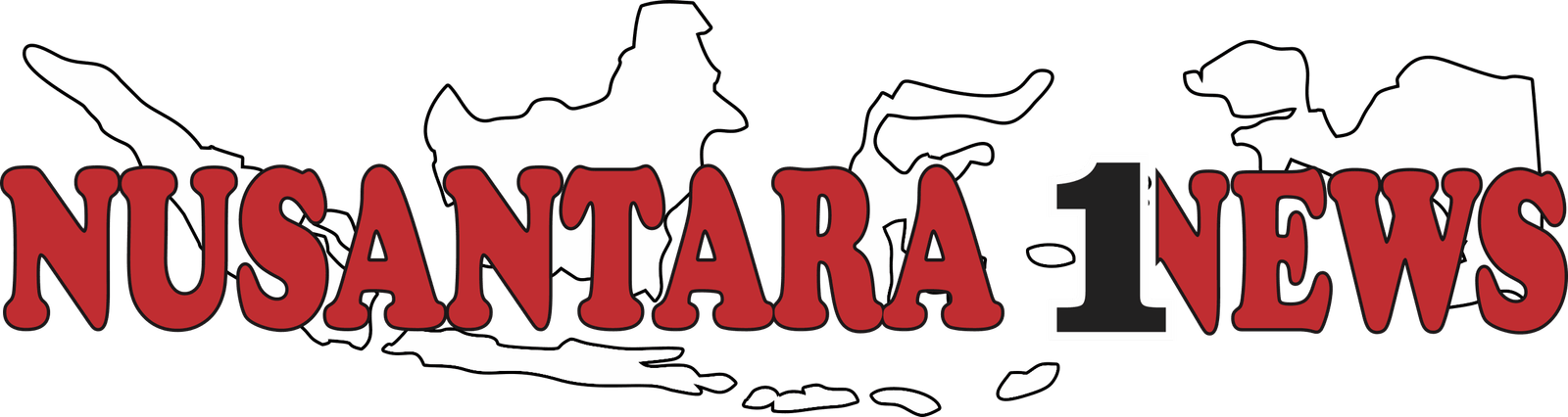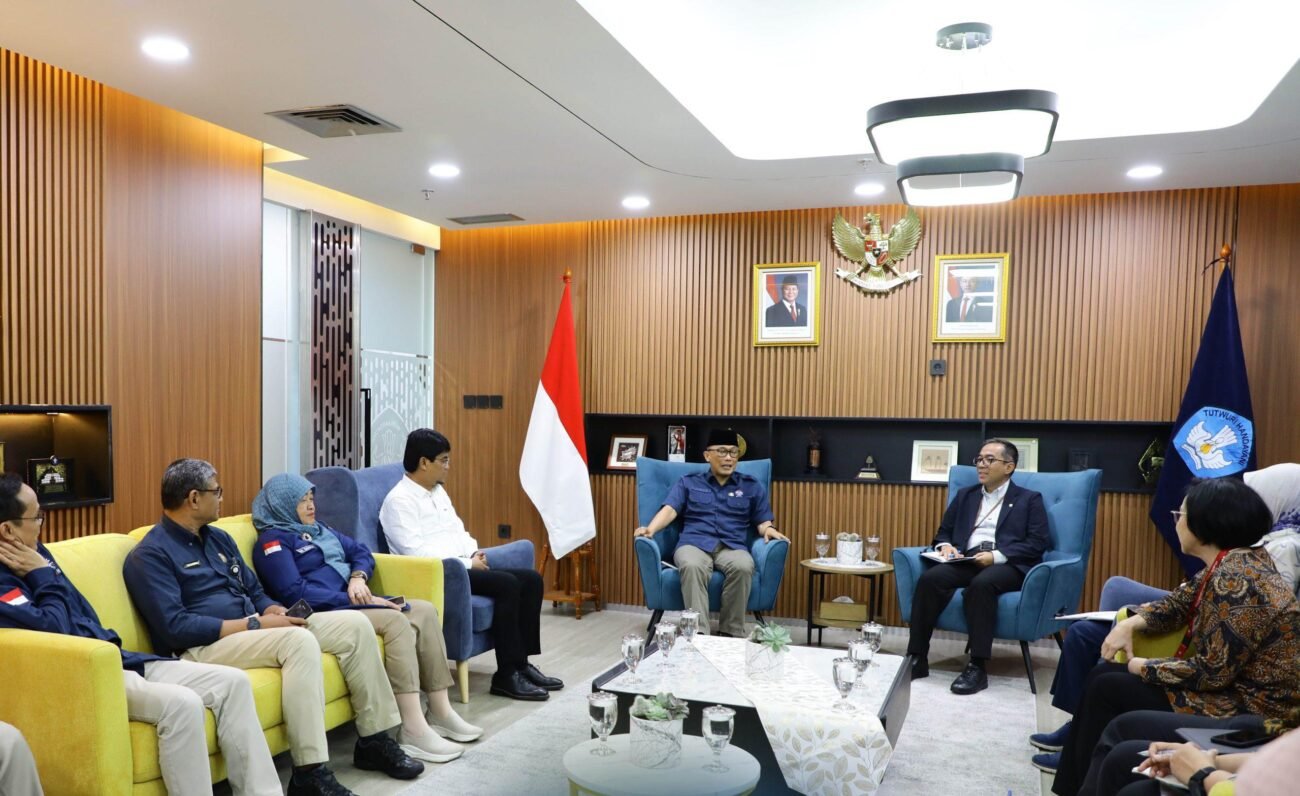Nusantara1News – Mongabay Di sisi kanan bukit Kampung Umera, Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, pemandangan hutan yang gundul tampak mencolok pada akhir Desember 2024. Sebuah eskavator berwarna kuning tampak aktif menggali tanah, mengeruk bijih nikel, lalu menumpuknya di lahan terbuka yang menjorok ke laut.
Alat berat itu terus bekerja tanpa henti, memindahkan material tambang ke dalam truk yang siap mengangkutnya ke pelabuhan tongkang di Teluk Inalo, yang terletak persis di samping bukit. Saat truk melaju, debu tebal berhamburan di udara.
Baca Juga : APBD 2025 Riau Alami Defisit Rp 1,3 Triliun, DPRD Minta Banggar Tinjau Ulang
Sementara itu, di balik perkampungan, hutan perbukitan juga mengalami nasib serupa. Pepohonan yang dahulu rimbun kini nyaris lenyap, hanya menyisakan beberapa batang yang tersisa. “Itu area tambang nikel PT Bartra Putra Mulia (BPM),” ujar Kepala Kampung Umera, Abdul Manan Magtiblo, sembari menunjuk ke arah bukit yang telah diratakan.
Aktivitas tambang ini dimulai sejak tahun 2020, dan sejak saat itu, warga mulai merasakan dampak buruknya. Mata air yang dahulu mengalir di bawah bukit, sekitar tiga kilometer dari desa, kini banyak yang mengering.
Bukan hanya sumber air, situs-situs keramat juga terdampak. Manan menjelaskan bahwa para tetua adat terpaksa memindahkan tempat sakral tersebut keluar dari wilayah konsesi perusahaan, melalui serangkaian ritual adat. “Perusahaan meminta agar situs keramat itu direlokasi,” katanya.
Izin usaha pertambangan (IUP) BPM sendiri diterbitkan pada tahun 2013 oleh mantan Bupati Halmahera Tengah, Al Yasin Ali. Luas konsesi yang diberikan mencapai 1.850 hektar dan berlaku hingga tahun 2033.
Warga setempat mengaku tak pernah dilibatkan dalam proses perizinan tersebut. Padahal, lahan yang kini dieksploitasi merupakan tanah ulayat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, baik untuk berkebun maupun memanfaatkan hasil hutan. Sejumlah marga yang memiliki hak atas wilayah tersebut di antaranya Umlil, Umsandin, Umsipyat, Magimai, Magtublo, dan Magpo.
Konflik Hak Ulayat di Pulau Gebe: Lahan Adat Tergerus, Janji Ganti Rugi Tak Kunjung Terpenuhi
Hak ulayat dalam masyarakat adat memiliki sifat komunal, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Helza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution (2021). Prinsip ini dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Di Kampung Umera, kepemilikan lahan secara komunal masih dipraktikkan hingga kini. Tanah warisan marga dapat dimanfaatkan bersama oleh warga lain, asalkan saling memberi tahu. “Siapa saja dari kampung bisa menggunakan tanah atau mengambil hasil kebun, yang penting kasih tahu pemiliknya,” ujar seorang warga.
Seorang pria berusia 70 tahun mengajak Mongabay berkeliling kebunnya dengan mobil pikap, melewati jalan setapak yang dikelilingi deretan pohon kelapa, kakao, cengkih, dan pala hingga ke rumpun sagu.
Namun, pemetaan menggunakan aplikasi Avenza Maps menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah adat kini masuk dalam konsesi tambang PT Bartra Putra Mulia (BPM). Di beberapa lokasi, sedimen lumpur dari aktivitas tambang mulai menggenangi kebun sagu, menyebabkan kerusakan yang semakin parah.
Material lumpur tersebut, menurut warga, berasal dari kawasan tambang di bukit. “Hampir semua rumpun sagu warisan marga di Kampung Umera ini sudah rusak,” ujar seorang warga. Di kebun sagu milik marga Magtublo di Hol dan Kayai, sekitar sembilan hektare telah terdampak.
Ramalan Abubakar Magpo mengungkapkan hal serupa. Ia bahkan tidak lagi bisa mengambil sagu di hutan Wagob karena tanah warisan marga Magpo telah tertutup sedimen, seperti halnya lahan milik marga lain.
Masalah ini bukan hal baru. Sejak 2021, dampaknya semakin dirasakan warga. “Kami tidak bisa lagi mengambil sagu untuk diolah,” kata Ramalan. Kerusakan akibat tambang tak hanya berdampak pada kebun, tetapi juga meluas ke Teluk Inalo, yang menyebabkan perubahan warna air laut.
Sebelum mulai beroperasi, perusahaan sempat bertemu dengan warga untuk mengukur batas tanah tiap marga. Saat itu, mereka berjanji akan memberikan ganti rugi bagi lahan yang terdampak.
“Kita tinggal tunjuk lokasi yang rusak, nanti akan ada tim yang menilai dan menentukan pembayaran sesuai permintaan pemiliknya,” ungkap seorang warga, mengingat janji yang diberikan. Namun, hingga kini, kompensasi tersebut tak kunjung terealisasi. “Sampai sekarang belum ada pembayaran,” tambahnya.
Di Maluku Utara, kasus seperti ini kerap terjadi. Husen Alting dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No.2 (2013) mengungkap bahwa dalam konflik kepemilikan lahan, perusahaan dan pemerintah sering menggunakan mekanisme litigasi yang mengandalkan bukti formal. Sementara itu, masyarakat lebih mengutamakan jalur non-litigasi dengan pembuktian berbasis hukum adat, bukan sertifikat tanah.
Mongabay telah berupaya meminta klarifikasi dari pihak perusahaan terkait persoalan ini. Namun, hingga awal Februari, surat permohonan wawancara yang dikirimkan kepada humas BPM, Jalaludin Ramalan, tidak mendapat tanggapan.
Rumpun Sagu yang Hilang: Hancurnya Sumber Pangan dan Tradisi di Kampung Umera
Bagi masyarakat Kampung Umera, sagu bukan sekadar sumber penghidupan, tetapi juga bagian penting dari tradisi adat. Salah satu ritual yang bergantung pada sagu adalah prosesi jelang pernikahan. Ramalan Abubakar Magpo menjelaskan bahwa saat seorang lelaki melamar kekasihnya, ia wajib membawa tiga hingga empat tumang—wadah dari pelepah daun rumbia—yang berisi pati sagu.
Sagu dengan nama ilmiah Metroxylon sagu Rottb. ini dikemas dalam tumang berukuran besar sebagai bagian dari syarat lamaran. “Setelah seserahan terpenuhi, barulah prosesi adat pernikahan bisa berlangsung,” jelasnya.
Namun, kini keberadaan rumpun sagu di Kampung Umera terancam akibat aktivitas tambang. Abubakar mengaku cemas melihat lahan sagu warisan marga Magpo dan Magimai di Teluk Smingit, seluas 30 hektare, rusak parah karena terendam lumpur. Wilayah yang berbatasan dengan Kampung Sanafi Kacepo ini terdampak akibat operasi tambang nikel PT Anugerah Sukses Mining (ASM) yang menguasai 504 hektare lahan.
Sejak 2021, pengerukan nikel di lokasi tersebut membuat pohon-pohon sagu tak lagi bisa dimanfaatkan karena tertutup sedimen. Setelah merusak lahan, perusahaan menghentikan operasinya, meninggalkan lahan yang gundul dan tak lagi produktif.
Sebelumnya, para ibu di Kampung Umera memanfaatkan daun sagu untuk membuat anyaman, namun tradisi ini kini sulit ditemukan karena bahan bakunya semakin langka.
“Tambang ASM adalah yang paling merusak. Marga Magpo sama sekali tidak dilibatkan sejak awal, dan hak kami atas tanah di Smingit diabaikan begitu saja,” keluh Abubakar.
Mongabay mencoba meminta konfirmasi dari pihak ASM mengenai klaim kerusakan ini. Namun, sejak awal Februari 2025, permohonan wawancara yang dikirimkan tidak mendapatkan respons.
Kerusakan lingkungan di Kampung Umera hanyalah gambaran kecil dari kehancuran yang terjadi di Pulau Gebe. Selama beberapa dekade terakhir, industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan menggerus hak ulayat masyarakat adat.
Mimin Dwi Hartono, Analis Kebijakan Madya di Komnas HAM RI, menegaskan bahwa perusahaan seharusnya menghormati hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat adat yang sangat bergantung pada alam.
“Jika ada hak masyarakat adat, mereka bisa mengajukan klaim berdasarkan sejarah dan asal-usul, meskipun tidak memiliki dokumen hukum seperti sertifikat tanah,” jelasnya.
Jejak Eksploitasi Nikel di Pulau Gebe
Eksploitasi nikel di Pulau Gebe dimulai sejak 1968, ketika Indeko Indonesia Development Company pertama kali membuka operasi tambangnya. Pada masa itu, Jou Jau (Perdana Menteri) Kesultanan Tidore, H.M. Amin Faaroek, turut menyaksikan proses awal penambangan tersebut.
Setelah perusahaan asal Jepang tersebut menghentikan aktivitasnya, PT Antam mengambil alih pada tahun 1978 dan menjalankan operasinya hingga 2004. Selama lebih dari dua dekade, perusahaan ini mengubah lanskap Pulau Gebe secara drastis. Perkebunan warga yang sebelumnya dipenuhi kelapa, cengkih, dan sagu tergeser oleh area pertambangan nikel.
Sebuah riset dari Foshal, Trend Asia, dan YLBHI (2024) mengungkap bahwa keberadaan tambang Antam menyisakan trauma bagi masyarakat setempat. Ketika operasi pertambangan berakhir, layanan air bersih dan listrik yang dulu disediakan perusahaan juga ikut terhenti.
Namun, eksploitasi sumber daya di Pulau Gebe tidak berakhir begitu saja. Saat ini, tujuh konsesi nikel masih aktif beroperasi di pulau yang memiliki luas 224 kilometer persegi ini. Salah satunya adalah PT Mineral Jaya Moligana (MJM) yang memiliki konsesi seluas 914,50 hektare di Blok Kaf.
Seperti halnya wilayah Kampung Umera yang berada dalam konsesi BPM, Blok Kaf juga merupakan bagian dari tanah adat Kampung Sanof Kacepo. Dalam bahasa Gebe, Sanof atau Sanaf berarti tombak.
Seorang warga setempat, Hamdala, menjelaskan bahwa daerah ini dikenal sebagai El atau Gunung Kaf, yang dipercayai masyarakat sebagai tempat sakral bagi Kampung Sanof Kacepo. “Di bukit Kaf, ada goa-goa yang sejak dulu dianggap keramat oleh warga,” ungkapnya.
Pulau Gebe sendiri telah dihuni sejak zaman purbakala oleh dua kelompok suku, yaitu Wetef dan Wagiya. Masyarakat awal ini percaya pada kekuatan supranatural dan tinggal di dalam gua sebelum akhirnya bermigrasi ke pesisir seiring dengan perubahan budaya.
Dalam bahasa Tidore, kata Gebe berasal dari dua suku kata: Ge yang berarti “di situ” dan Be yang berarti “di mana.” Sedangkan dalam bahasa Gebe, Geb berarti “lunas perahu.”
Kampung Sanof Kacepo diyakini sebagai pemukiman pertama di Pulau Gebe, berbeda dengan Kampung Umera yang muncul lebih belakangan. Masyarakat di Kampung Kacepo terbagi dalam empat kelompok marga, yakni Umsipiyat, Umsero, Umlatti, dan Fapofapo. Hak ulayat mereka berbatasan dengan Kampung Umera, mulai dari Sungai Tuan hingga Tanjung Safa.
Hamdala menambahkan bahwa setelah kampung-kampung ini berstatus desa, batas wilayah ulayat mulai mengikuti aturan administrasi desa yang ditetapkan pemerintah. “Sekarang kami mencoba memisahkan wilayah administrasi desa dengan hak ulayat. Dengan begitu, ketika tambang berhenti beroperasi, masyarakat bisa kembali mengelola tanah adatnya,” ujarnya.
Abdulajid Fatah Umsipiyat, salah satu tetua adat di Kampung Sanof Kacepo, menjelaskan bahwa sistem adat yang diterapkan di sana masih mengikuti aturan Sangaji, sistem yang diperkenalkan oleh Kesultanan Tidore ke Pulau Gebe. Pada masa lalu, wilayah seperti Maba, Wasilei, Bicoli, dan Gebe dikenal sebagai Gam Ramrange, yakni daerah otonom yang berada di bawah Kesultanan Tidore.
Sultan Tidore ke-23, Achmad Mansur Sirajuddin Syah, yang berkuasa pada 1821-1856, pernah mengeluarkan surat yang mengakui hak ulayat masyarakat Pulau Gebe. Dokumen ini bertanggal 6 Rajab 1241 Hijriyah dan menegaskan bahwa seluruh wilayah Pulau Gebe, baik di utara, selatan, timur, maupun barat, merupakan bagian dari Kesultanan Tidore.
Husen Alting, Guru Besar Hukum Adat dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, menyatakan bahwa masyarakat hukum adat memiliki tiga unsur utama: keberadaan komunitas adat, wilayah hukum adat, dan pranata adat.
“Selama ada sistem dan komunitasnya, maka hak masyarakat adat tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam hukum adat, tidak ada tanah yang tidak bertuan,” tegasnya.
Di Pulau Gebe, sistem adat ini masih terus berkembang mengikuti dinamika zaman. Keberadaan Sangaji Gebe dan Sangaji Patani, serta peran Gimelaha (kepala kampung), menjadi bukti bahwa pranata adat tetap eksis meskipun wilayah tersebut telah lama mengalami eksploitasi industri pertambangan.
Deforestasi Akibat Tambang Nikel
Pada suatu sore, perbukitan di Pulau Fau masih dipenuhi hiruk-pikuk aktivitas tambang. Truk-truk pengangkut nikel lalu-lalang, sementara ekskavator terus menggali tanah, menyebabkan bukit di ujung pulau semakin menyusut.
Pulau kecil yang merupakan bagian dari Kepulauan Gebe ini hanya berjarak sekitar 475 meter dari Desa Kacepo. Sejak Juni 2024, PT Aneka Niaga Prima (ANP) mulai menambang di lahan seluas 459,66 hektare.
Sebelum aktivitas pertambangan dimulai, kelompok pegiat lingkungan telah menyuarakan penolakan. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan ekosistem, gangguan terhadap biota laut, hingga pencemaran lingkungan.
Saat mengunjungi Pulau Gebe pada pertengahan Desember 2024, Mongabay mendapati pemandangan aktivitas tambang yang masih berlangsung. Di malam hari, tongkang-tongkang terlihat hilir-mudik di perairan, mengangkut ore nikel dari pulau itu.
Seorang pekerja tambang mengungkapkan bahwa hasil tambang dari Pulau Gebe dikirim ke IWIP. “Dibawa ke Weda,” ujarnya.
IWIP, atau Indonesia Weda Bay Industrial Park, adalah kawasan industri pengolahan logam yang berlokasi di Desa Lelief, Kecamatan Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Temuan ini juga diperkuat dalam laporan oleh Project Multatuli.
Di fasilitas IWIP, nikel diproses menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL). Pabrik ini disebut sebagai salah satu pusat pengolahan nikel dengan kapasitas terbesar di dunia.
Pembangunan kawasan industri tersebut merupakan bagian dari kebijakan hilirisasi nikel yang digagas pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Bijih nikel yang diolah di sana menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik.
Namun, di balik kebanggaan terhadap hilirisasi nikel, berbagai persoalan muncul di lapangan. Hak-hak masyarakat adat sering kali terabaikan, pencemaran lingkungan semakin meluas, dan deforestasi tak terhindarkan. Hal ini terungkap dalam riset yang dilakukan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) pada 2023.
Forest Watch Indonesia (FWI) juga mencatat dampak negatif dari aktivitas tambang ini. Data mereka menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2022-2023, Pulau Gebe kehilangan tutupan hutan seluas 62,61 hektare akibat ekspansi pertambangan nikel. Selain Gebe, tambang juga telah merambah beberapa pulau kecil lain, seperti Pulau Fau, Pulau Gee, Pulau Pakal, Pulau Mabuli, dan Pulau Malamala.
Baca Juga : KPU Riau Tetapkan Lima Panelis Debat Pilgub 2024, Tegaskan Netralitas
Anggi Putra Yoga, Manajer Kampanye, Advokasi, dan Media FWI, menyoroti konsesi tambang nikel yang tersebar di pulau-pulau kecil di Maluku Utara. Ia menilai bahwa eksploitasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K).
Tak hanya melanggar regulasi, pertambangan di pulau kecil juga meningkatkan risiko ekologis dan sosial. Dampak destruktifnya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam di pulau-pulau tersebut.
“Perusahaan dapat dengan mudah pergi setelah sumber daya mereka habis, tetapi masyarakat yang tinggal di sana akan menghadapi kesulitan karena kehilangan mata pencaharian dan sumber daya alam yang dulu mereka andalkan,” ungkap Anggi.